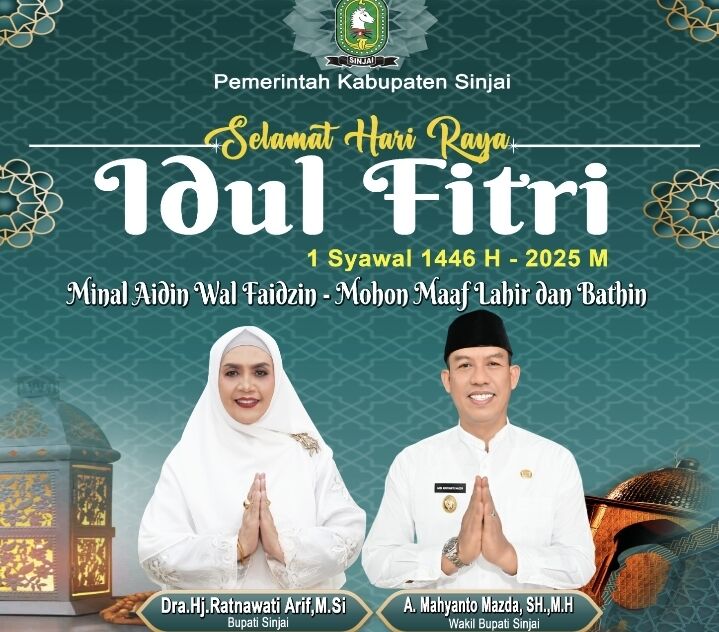Bagi masyarakat Suku Makassar di Sulawesi Selatan, lontara atau tala (borassus flabellifer) merupakan salah satu jenis pohon yang sangat familiar. Pohon lontara merupakan sejenis palem berbatang satu yang kuat dan kokoh dengan tinggi 15 hingga 30 meter. Batangnya ke arah ujung dan pangkal membesar dengan daun membentuk tajuk. Pelepah yang lebar serta pada bagian atas hitam.
Buahnya bulat peluru berdiameter 7-20 cm. Biasanya bergerombol dalam tandan dengan jumlah sekitar 20-an butir. Warnanya hitam kecokelatan.
Pohon lontara berbatang tunggal dengan ketinggian mencapai 15-30 m dan diameter batang sekitar 60 cm. Daunnya besar-besar mengumpul di bagian ujung batang membentuk tajuk yang membulat. Setiap helai daunnya serupa kipas dengan diameter mencapai 150 cm. Tangkai daun mencapai panjang 100 cm. Pohon lontara mampu hidup hingga 100 tahun lebih.
Lontara yang menurut Thecolourofindonesia sebagai flora identitas Sulawesi Selatan juga sering disebut dengan pohon siwalan. Flora ini termasuk jenis palma (pinang-pinangan). Hampir semua bagian pohonnya bisa dimanfaatkan. Mulai dari daun, batang, buah hingga hingga bunganya yang dapat disadap untuk diminum langsung sebagai legen (tuak) ataupun diolah menjadi gula merah. Tuak inilah yang oleh warga Jeneponto dijadikan bahan baku gula merah. Meproduksi gula merah dari tuak dilakukan secara turun-temurun di daerah ini meskipun secara konvensional. Produksi gula merah di Jeneponto menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat mencapai 16,437 ton per tahun.
Pohon ini banyak tumbuh di daerah kering. Di Indonesia, selain di Sulawesi Selatan, pohon ini juga tumbuh di Jawa Timur, Jawa Tengah bagian timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten sentra pohon lontara adalah Jeneponto. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Jeneponto (2016), luas areal perkebunan lontara mencapai 427,50 hektare. Pepohonan ini dominan tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Binamu, dan Kecamatan Bangkala. Di beberapa kecamatan lannya, populasi lontara tidak terlalu banyak.
Menurut sejarah, pohon ini pernah berjaya di era kejayaan Kerajaan Gowa. Masyarakat di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto menjadikan pohon ini sebagai tanaman penting di samping jagung atau padi. Pengawal Raja Gowa sering mengonsumsi ballo (tuak) sebagai minuman khas di samping air putih.
“Dahulu setiap daerah yang dikunjungi Raja Gowa atau pemangku adat kerajaan selalu ditanami pohon lontara. Tala Salapang atau sembilan pohon lontara yang ada di Makassar itu juga kemungkinan buah tangan pengawal kerajaan di masa lampau,” kata Bahtiar, pengamat kebudayaan Makassar.
Salah satu bukti kesejarahan pohon ini adalah tala salapang (sembilan pohon lontara) yang saat ini masih tumbuh di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Usianya sudah ratusan tahun. Jumlahnya memang sudah tidak utuh. Sisa tujuh batang. Karena sejarah batang ini pula, kawasan tersebut juga dinamai Jalan Tala Salapang. Konon menurut sejarah, tala salapang ini ditanam oleh kelompok pasukan kerajaan Gowa saat rehat dalam sebuah perjalanan dinas kerajaan.
Bachtiar menambahkan karena pohon bersejarah, pohon ini diabadikan sebagai logo atau lambang beberapa instansi. Salah satunya Kodam XIV Sultan Hasanuddin Makassar yang sebelumnya bernama Kodam VII Wirabuana. Logo pohon lontara terlihat dari baju seragam (uniform) prajurit Kodam XIV Sultan Hasanuddin. Karena itu pula, pada syukuran perubahan nama Kodam Wirabuana ke Sultan Hasanuddin, Oktober 2017 lalu dilakukan penanaman 40 ribu pohon lontara secara massal.
Pohon lontara memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Selain menghasilkan buah segar dan tuak (ballo), bagian-bagian lain dari pohon ini juga bisa menghasilkan uang. Daunnya bisa dibuat atap. Pelepahnya juga bisa dibuat pagar. Batangnya pun cukup kuat dijadikan balok atau tangga rumah kayu. Mayoritas rumah kayu di Jeneponto terutama yang di pelosok kampung, bahan bakunya menggunakan batang lontara. Mulai dari balok hingga tangga.
Memang selama ini masyarakat lebih banyak memanfaatkan buah dan tuaknya saja. Tuak atau ballo banyak diolah menjadi gula merah. Di Jeneponto, salah satu sentra lontara kini tumbuh beberapa kelompok tani perajin gula merah. Sayangnya pengelolaannya masih konvensional. Kelompok tani pembuat gula merah itu belum tersentuh teknologi. Bahan bakarnya kebanyakan menggunakan kayu bakar.
Bahkan profesi sebagai perajin gula merah itu sudah turun-temurun. Saharuddin, salah seorang pembuat gula merah di Paranglambere, Jeneponto mengaku memilih pekerjaan ini karena melanjutkan karier ayahnya. Setiap hari, Saharuddin memproduksi 70 hingga 100 hingga biji gula merah atau sekira 75 kilogram.
“Semula saya hanya bantu bapak ambil tuak dari pohon lontara. Akhirnya jadi tahu cara membuat gula merah. Setiap hari kami memproduksi gula merah. Tetapi jika musim hujan tiba, kami berhenti memproduksi karena tidak bisa manjat pohon lontara. Batang lontara licin saat musim hujan,” kata Saharuddin.
Perajin gula merah lainnya di kampung ini, Mukhtar menambahkan memproduksi gula merah merupakan profesi utama di samping bertani. Penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan ini juga lumayan. Minimal bisa menutupi biaya hidup dan ongkos sekolah tiga anaknya. Seperti Saharuddin, Muktar juga rata-rata memproduksi gula merah 75 kilogram per hari.
Di kampung ini, sebagian besar warganya berprofesi sebagai pembuat gula merah. Mereka membentuk kelompok tersendiri. Satu kelompok beranggotakan tujuh sampai sepuluh perajin. Setiap kelompok dibina pengusaha gula. Sang pengusaha inilah yang mengumpul dan membeli produksi gula merah dari perajin binaannya untuk selanjutnya dipasarkan.
Habibah, salah seorang pengusaha gula di kampung ini mengaku membina tujuh perajin gula. Selain memasarkan hasil produk kelompok binaannya, ia juga menyiapkan segala modal kerja dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Menyiapkan modal kerja untuk pengadaan sene (zat pemanis), kayu bakar, jeriken dan perlengkapan lainnya adalah kewajiban setiap pengusaha gula merah.
Model pemasaran gula merah di Jeneponto masih konvensional. Gula yang terkumpul setiap hari dijual ke pedagang di pasar tradisional. Harganya variatif. Mulai dari Rp3.500 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Tapi pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan dan musim hujan, harga gula merah di pasar kerap melonjak. Permintaan dan pemakaian konsumen pada waktu itu memang bertambah. Selain di pasar tradisional Jeneponto, gula merah juga banyak beredar di pasar-pasar tradisional di Makassar.
Proses pembuatan gula merah juga cukup rumit. Langkah pertama, perajin mengambil tuak di atas pohon lontara dengan cara memanjat. Setiap pohon yang menjadi sumber tuak dipasangi tongka (semacam gentong yang terbuat dari bambu). Rata-rata setiap perajin memanjat 20 hingga 30 batang lontara setiap hari. Tuak yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam kuali besar lalu dimasak hingga mendidih dan mengental. Karena warna cairan itu kemerah-merahan sehingga dinamakan gula merah. Setelah masak, cairan yang mengental itu dituang ke wadah tempurung lalu diangin-anginkan hingga kering. Jadilah gula merah.
Produksi gula merah tersebut tidak sepanjang tahun. Jika musim hujan tiba, perajin gula merah banting setir menjadi petani kebun. Faktor keamanan dan ketersediaan kayu bakar menjadi alasan utama para perajin gula merah istirahat saat musim hujan. Pembuat gula enggan memanjat pohon saat musim hujan karena batang pohon licin. Kayu bakar yang digunakan untuk memasak tuak juga terbatas saat musim hujan.
Meski memiliki potensi ekonomi besar dengan rata-rata produksi 16 ribu ton per tahun, perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan lontara dianggap masih minim. Beberapa perajin gula merah mengaku tidak pernah mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah. Mereka mengembangkannya secara otodidak. Tidak mengherankan jika kemasannya sangat konvensional.
Pembina kelompok tani perajin gula merah, Mukhtar Tompo sudah beberapa kali mengusulkan pembinaan secara kontinyu kepada perajin gula merah. Tidak saja dalam hal kemasan, tetapi juga penyiapan modal kerja. Menurut dia, pemerintah daerah sudah harus turun tangan membina para perajin gula merah tersebut.
“Gula merah ini menjadi komoditas spesifik dari Jeneponto. Harusnya pemerintah daerah lebih care dan perhatian terhadap perajin gula. Kemasannya diperbaiki dan butuh sentuhan teknologi untuk bahan bakarnya. Mungkin sudah saatnya perajin gula menggunakan batu bara. Bukan kayu bakar lagi,” katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, Muhammad Sofyan juga mengakui besarnya potensi gula merah. Ia mengatakan pemerintah daerah sejauh ini sudah membina para perajin gula merah tersebut. Tetapi memang belum terlalu maksimal. Ke depan, kata dia, pemda sudah membuat perencanaan untuk pendampingan kelompok tani perajin gula yang tersebar di beberapa kecamatan di daerah ini.
Di samping perhatian terhadap kelompok perajin gula merah, hal penting lainnya yang juga membutuhkan perhatian serius adalah pelestarian lontara yang menjadi sumber utama gula merah. Mengapa? Belakangan ini ada kecenderungan populasi pohon lontara semakin berkurang. Pemanfaatannya tidak sebanding dengan pelestariannya. Penebangan lontara untuk kepentingan bahan baku rumah terus terjadi. Sementara di lain sisi, pembudidayaannya minim. Di Jeneponto dan daerah-daerah sentra lontara saat ini tidak lagi ditemukan ada budi daya pengembangan pohon ini.
Beberapa warga mengaku enggan membibitkan lontara karena bisa tumbuh sendiri. Anakan pohon lontara biasanya tumbuh di bawah pohon lontara saat musim hujan. Selama ini, masyarakat lebih banyak memanfaatkan anakan itu dalam membudidayakan lontara. Anakan yang sudah setinggi 50 cm ditanam dengan cara memindahkannya ke tempat lain.
Fenomena ini juga mengundang dosen Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar, Muhammad Fatahnur, MHut, untuk melakukan riset. Menurut dia, jika tidak mendapat perhatian serius, pohon ini terancam punah. Faktanya, kata dia, saat ini sudah tidak ada pembibitan tanaman lontara. 40 ribu pohon yang ditanam Kodam XIV Sultan Hasanuddin, Oktober lalu bukan dari bibit yang sudah disiapkan melainkan diambil dari anakan lontara yang tumbuh liar di sekitar induknya.
“Pohon-pohon anakan ini kebanyakan tidak memiliki daya tahan yang kuat karena akarnya rentan putus. Makanya banyak lontara tidak berusia panjang karena diambil dari anakan. Harusnya yang ditanam itu dibibitkan lebih dahulu,” katanya. (fachruddin palapa)
Lontara, Pohon Bersejarah yang Terancam Punah

×