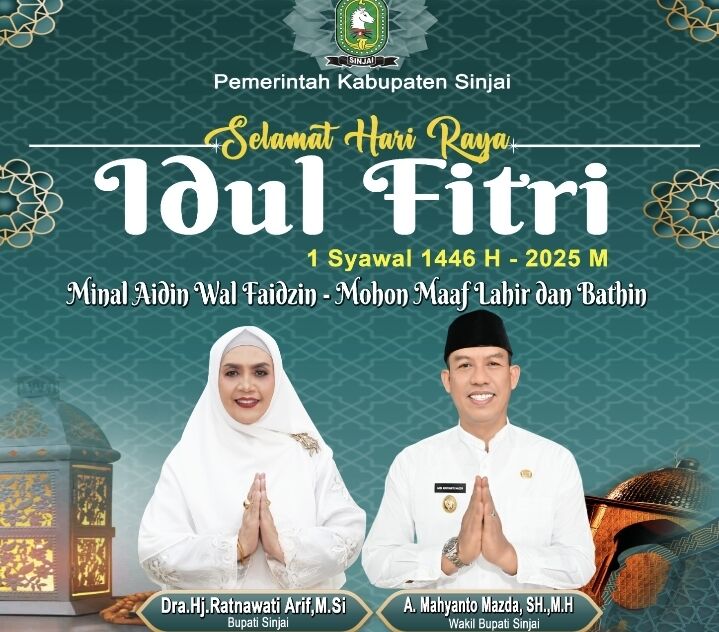WACANA kampus mengelola atau memegang konsesi tambang merupakan topik yang menarik dan cukup kompleks. Dalam memberi pendapat terkait hal ini, kita perlu menilik dari berbagai perspektif.
Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Selain memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sumber daya mineral dan batubara pun menjadi tulang punggung perekonomian.
Namun, seringkali pengelolaan sumber daya alam ini tidak optimal dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta ketimpangan sosial. Entah itu dari segi perizinan, hingga pengelolaan dan pengawasannya.
Bila kemudian kampus diberi peran mengelola tambang, ada potensi besar untuk menciptakan model pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan berbasis riset. Terlebih bagi kampus yang memiliki Prodi Teknik Pertambangan, misalnya.
Kampus dapat mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam ekstraksi serta pemrosesan mineral. Misalnya, mereka bisa mengembangkan metode penambangan yang mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, atau teknologi yang mampu mengurangi emisi karbon dari proses pertambangan.
Selain itu, kampus juga dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam industri tambang, yang seringkali terabaikan oleh perusahaan tambang komersial.
Namun, perlu dipikirikan pula bahwasanya ada tantangan besar yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah konflik kepentingan antara tujuan akademis dan tujuan komersial. Kampus memiliki misi utama untuk mendidik, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat.
Dalam mengelola tambang, ada faktor ekonomi yang memerlukan perhatian khusus. Jika kampus berpartisipasi dominan dalam pengelolaan tambang secara komersial, dikhawatirkan tujuan akademisnya bisa terganggu. Ada risiko terganggunya keseimbangan antara nilai akademik dan komersial, di mana kampus bisa saja lambat laun atau secara tidak sadar dalam prosesnya justru berorientasi pada keuntungan finansial, sehingga mengabaikan prinsip pendidikan dan keberlanjutan.
Proses pertambangan merupakan bisnis jangka panjang, sehingga kampus harus menjalankan berbagai tahapan dengan estimasi waktu 5-10 tahun. Pada rentang waktu itu, perguruan tinggi pun harus mengeluarkan modal sebelum mendapatkan uang dari hasil tambangnya.
Sejauh mana kampus siap? Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran bahwasanya concern dari universitas harus tetap berfokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi saja.
Selanjutnya, pengelolaan tambang oleh kampus juga dapat memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada di beberapa daerah penghasil tambang. Banyak daerah di Indonesia yang selama ini merasa terpinggirkan akibat kurangnya manfaat yang diterima dari aktivitas pertambangan.
Jika universitas yang mengelola tambang, perlu ada jaminan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan memberikan dampak positif yang merata bagi masyarakat sekitar, bukan hanya menguntungkan pihak universitas atau perusahaan tambang yang terlibat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil tambang juga harus dijaga agar tercipta kesejahteraan yang adil. Ujung dari pemikiran ini bermuara pada keterlibatan kampus dalam tambang “hanya akan menambah konflik terbuka dengan masyarakat” yang dirugikan oleh aktivitas ekstraktif tersebut.
Kampus juga harus menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam ini agar tidak terjebak dalam praktik-praktik korupsi atau eksploitasi berlebihan.
Selama ini mahasiswa merupakan bagian yang cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Akan timbul pemikiran “berpotensi matinya daya kritis kampus yang umumnya diwakili oleh mahasiswa terhadap pemerintah dengan adanya izin tambang”. Bagaimana pun masyarakat membutuhkan pihak netral. Salah satunya yakni mahasiswa dari kampus-kampus tujuan.
Atau jika memang nantinya disepakati dan direalisasikan, mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas independen dalam pengelolaan tambang yang dilakukan oleh universitas. Dalam hal ini, mahasiswa bisa terlibat dalam proses pemantauan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Melalui organisasi mahasiswa, mereka dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau bahkan lembaga negara untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang diterapkan oleh universitas tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
Ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan atau eksploitasi berlebihan yang kadang terjadi dalam industri tambang. Tapi kembali lagi, apakah mahasiswa kiranya berani utk bertindak demikian?, Menempatkan diri di tengah-tengah (netral) antara masyarakat dan rumahnya sendiri, yakni kampus sebagai pengelola tambang.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat peluang bagi kampus untuk berperan dalam mengelola tambang dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan, namun hal ini membutuhkan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat. Universitas harus bisa memastikan bahwa misi akademik tetap terjaga, sementara manfaat ekonomi dan sosial dari pengelolaan tambang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai yang termaktub pada pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945.
Jika dapat dilaksanakan dengan benar, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam sektor pertambangan bisa menjadi model yang lebih bertanggung jawab dan inovatif di Indonesia. Melihat wacana ini juga masih sekadar usulan pada saat pembahasan revisi UU Minerba. Semoga dapat dipertimbangkan secara matang serta memastikan partisipasi publik harus terwakilkan secara menyeluruh. (mg4)